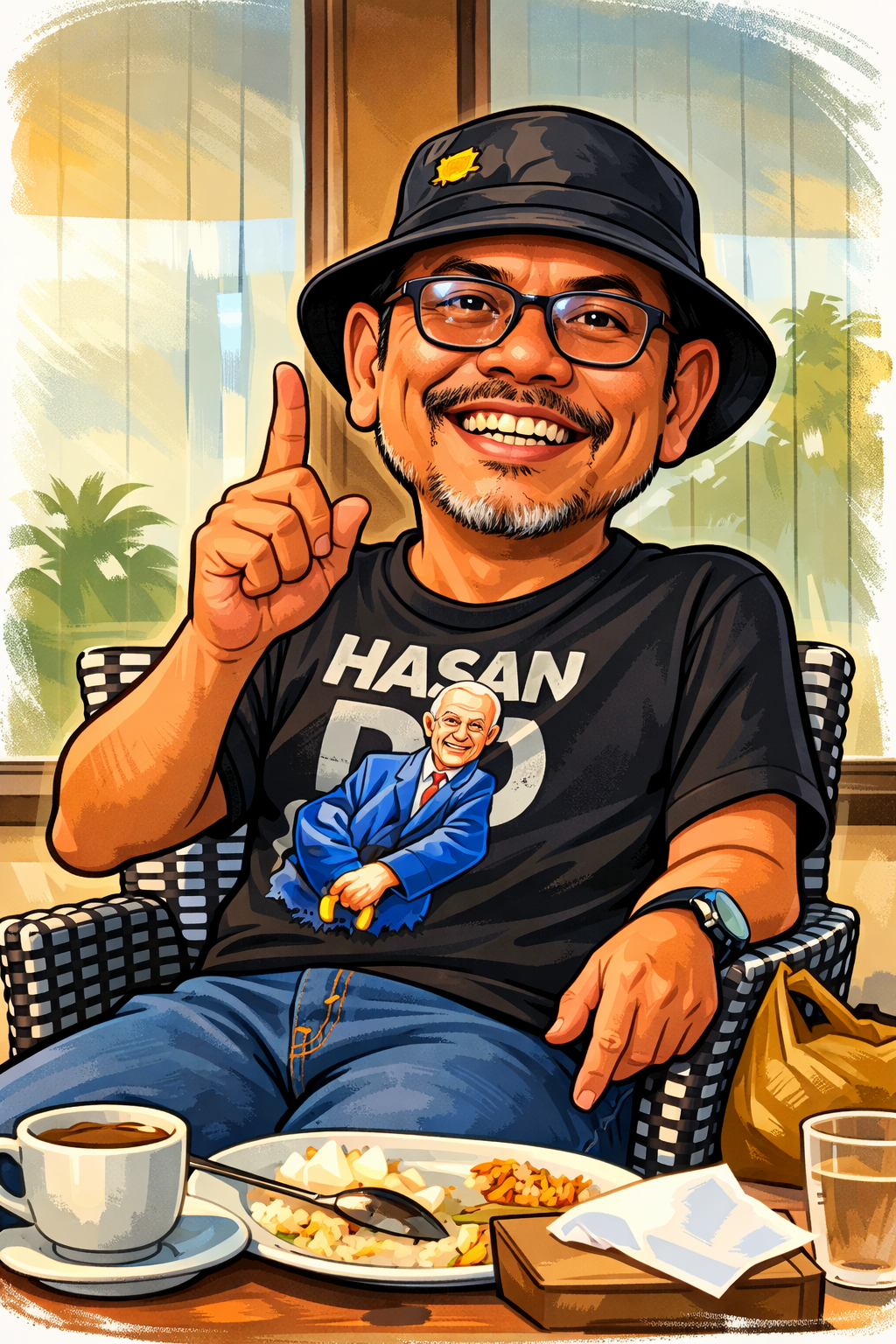Infonewsnusantara.com — Dalam praktik kepemimpinan publik, perbedaan antara karya dan gaya semakin mudah dikenali. Ada pejabat yang bekerja dalam senyap namun meninggalkan hasil nyata, dan ada pula yang gemar tampil ke depan dengan berbagai gaya, tetapi miskin capaian substansial. Fenomena ini bukan sekadar persoalan karakter, melainkan cerminan kualitas kepemimpinan dan etika jabatan.
Secara normatif, jabatan publik adalah amanah yang menuntut tanggung jawab, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak terletak pada seberapa sering ia tampil di ruang publik, melainkan pada sejauh mana kebijakan dan tindakannya memberi dampak nyata. Namun dalam realitas birokrasi kontemporer, sebagian pejabat justru lebih sibuk membangun narasi tentang kerja daripada bekerja itu sendiri.
Gaya komunikasi yang berlebihan mulai dari retorika panjang, slogan bombastis, hingga pencitraan seremonial sering kali menjadi pengganti kerja teknokratis yang seharusnya menjadi prioritas. Dalam kondisi demikian, publik lebih sering disuguhi simbol dan pernyataan, sementara persoalan mendasar justru berjalan di tempat.
Menariknya, pola ini kerap berulang pejabat yang banyak gaya cenderung cepat menunjukkan emosi ketika dikritik. Kritik yang seharusnya dipahami sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi justru dipersepsikan sebagai serangan personal. Alih-alih merespons secara substantif, yang muncul adalah sikap defensif, nada tinggi, bahkan upaya membungkam kritik. Hal ini menunjukkan rapuhnya kepercayaan diri dalam menjalankan amanah jabatan.
Sebaliknya, pejabat yang banyak karya umumnya lebih tenang dalam menghadapi kritik. Ia memahami bahwa kritik adalah konsekuensi logis dari kekuasaan publik. Dalam perspektif akademis, kematangan kepemimpinan tercermin dari kemampuan mengelola perbedaan pendapat tanpa emosi berlebihan. Karya yang nyata memberi ruang untuk berdialog, sementara gaya tanpa isi melahirkan kegelisahan.
Dominasi gaya tanpa karya tidak hanya merugikan publik, tetapi juga merusak budaya organisasi. Ketika pencitraan lebih dihargai daripada prestasi, orientasi kinerja melemah. Aparatur menjadi ragu untuk bekerja substansial karena yang dinilai bukan hasil, melainkan penampilan. Birokrasi pun tumbuh simbolik, namun rapuh secara fungsional.
Dalam sistem demokrasi, pejabat publik harus menyadari bahwa kritik bukan ancaman, melainkan instrumen perbaikan. Media cetak memiliki peran penting untuk mengingatkan bahwa kemarahan terhadap kritik bukanlah tanda kewibawaan, melainkan sinyal lemahnya kinerja. Wibawa sejati lahir dari hasil kerja yang terukur dan keberanian bertanggung jawab.
Pada akhirnya, publik akan selalu mampu membedakan siapa yang sibuk menghasilkan karya dan siapa yang sibuk mempertahankan gaya. Gaya akan cepat pudar, emosi akan segera berlalu, tetapi karya atau ketiadaannya akan menjadi catatan yang paling jujur dalam menilai kepemimpinan.